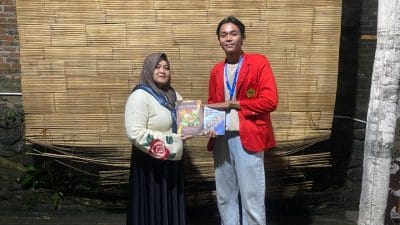Pendahuluan: Paradoks Kemerdekaan dalam Pendidikan
Sejak diluncurkan pada 2019, program “Merdeka Belajar” telah menjadi jargon utama dalam transformasi pendidikan nasional. Melalui kurikulum yang fleksibel, otonomi belajar, dan penguatan karakter, Merdeka Belajar digadang-gadang sebagai solusi atas sistem pendidikan Indonesia yang selama ini kaku dan tidak relevan. Namun, pertanyaannya: apakah anak Indonesia benar-benar merdeka dalam proses belajarnya?
Di balik semangat kebijakan ini, masih banyak siswa yang mengalami keterbatasan infrastruktur, kualitas guru, hingga “learning loss” pasca-pandemi. Alih-alih merdeka, sebagian besar peserta didik justru terjebak dalam sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dan konteks mereka.
Akar Masalah: Ketimpangan Akses dan Kualitas Pembelajaran
Menurut laporan Bank Dunia (2023), siswa Indonesia mengalami learning loss setara satu tahun ajaran akibat pandemi COVID-19. Meski proses pembelajaran kembali berlangsung tatap muka, pemulihan tidak berjalan merata. Data Kemendikbudristek (2024) menyebutkan bahwa lebih dari 52% sekolah dasar di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tidak memiliki perpustakaan, dan lebih dari 30% belum memiliki toilet yang layak.
Jika Merdeka Belajar menuntut eksplorasi, diskusi, dan literasi sebagai metode utama, bagaimana bisa anak-anak di wilayah tanpa internet, buku, bahkan guru tetap, mengeksplorasi ide-ide besar? Dalam realitas ini, kemerdekaan belajar menjadi retorika yang sulit diterjemahkan di lapangan.
Problem Kritis: Kurikulum Merdeka, Guru Belum Siap
Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas dan pembelajaran berbasis projek. Namun, laporan INOVASI dan Bappenas (2024) menyebutkan bahwa 44% guru belum memahami pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi, dan belum siap menyusun modul pembelajaran mandiri.
Guru adalah ujung tombak reformasi kurikulum. Jika mereka belum didukung dengan pelatihan, fasilitas, dan pendampingan yang memadai, maka implementasi Merdeka Belajar tidak lebih dari perubahan administratif semata. Bahkan, tidak sedikit guru yang masih mengandalkan metode hafalan dan evaluasi berbasis kuantitas nilai, bukan pemahaman mendalam.
Ketimpangan Digital: Kemerdekaan yang Tak Setara
Transformasi digital menjadi tulang punggung Merdeka Belajar. Namun, realitas menunjukkan bahwa digital divide masih menjadi hambatan besar. Data APJII (2024) menyatakan bahwa 30% wilayah Indonesia belum memiliki akses internet stabil. Di sisi lain, pemanfaatan platform seperti Rapor Pendidikan dan PMM (Platform Merdeka Mengajar) belum merata karena kendala teknis dan kurangnya pelatihan.
Maka, kemerdekaan belajar berbasis teknologi justru memperbesar ketimpangan. Anak-anak di kota besar bisa menikmati konten interaktif, sementara anak-anak di wilayah rural masih harus berbagi satu buku untuk tiga siswa, tanpa listrik pada malam hari.
Analisis Kritis: Merdeka Belajar atau Beban Belajar?
Model komunikasi edukatif seperti Gagne dan Briggs menyarankan bahwa pembelajaran efektif harus memperhatikan kesiapan peserta didik, motivasi, dan lingkungan belajar. Sayangnya, Merdeka Belajar terlalu menekankan kemandirian tanpa mempertimbangkan realita sosial-ekonomi siswa. Akibatnya, siswa yang belum siap justru merasa terbebani karena harus belajar mandiri tanpa bimbingan dan sumber belajar yang memadai.
Di sisi lain, Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Dalam konteks Indonesia, belum semua anak mengalami pendidikan sebagai proses pemerdekaan; masih banyak yang sekadar mengejar nilai untuk lolos ujian atau masuk sekolah favorit.
Solusi dan Rekomendasi
Agar Merdeka Belajar menjadi kenyataan dan bukan sekadar slogan, beberapa langkah strategis perlu diambil:
- Pemerataan akses infrastruktur dasar pendidikan seperti perpustakaan, toilet, dan konektivitas internet.
- Penguatan pelatihan guru secara berkelanjutan, terutama untuk guru di daerah non-perkotaan agar mampu menjalankan Kurikulum Merdeka secara bermakna.
- Penyederhanaan platform digital pendidikan agar tidak membebani guru dan siswa secara teknis.
- Evaluasi partisipatif dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam menilai efektivitas Merdeka Belajar di masing-masing daerah.
- Integrasi pendekatan lokal dan kearifan budaya dalam proyek pembelajaran, agar kurikulum tidak menjadi beban asing bagi siswa.
Penutup: Jalan Menuju Kemerdekaan yang Sesungguhnya
Merdeka Belajar adalah cita-cita mulia. Namun, tanpa dukungan nyata pada ekosistem pendidikan mulai dari guru, siswa, infrastruktur, hingga kurikulum kontekstual kemerdekaan itu hanya akan dinikmati oleh segelintir kelompok. Sementara mayoritas anak Indonesia masih harus berjuang, bukan hanya untuk memahami pelajaran, tapi untuk mendapatkan hak belajar yang layak. Maka, pertanyaannya tetap relevan: apakah anak Indonesia benar-benar sudah merdeka dalam belajar?
Penulis: Andika Salsa Dewi