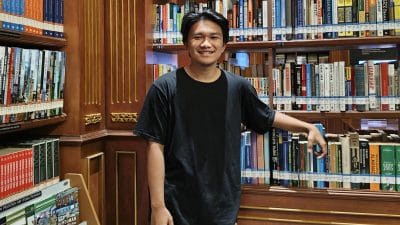EDISIKINI.COM, Babel — Fenomena diskriminasi rasial di lingkungan pendidikan kembali menjadi perbincangan publik. Meski institusi sekolah sering dipandang sebagai ruang pembentukan karakter dan toleransi, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak siswa yang menerima perlakuan berbeda karena warna kulit, bahasa daerah, suku, hingga identitas etnis tertentu. Rasisme tak selalu hadir melalui kekerasan fisik; bentuk yang paling sering terjadi justru berupa candaan, stereotip, dan labeling yang dianggap remeh.
Sekolah idealnya menjadi ruang yang aman, adil, dan mendukung perkembangan seluruh peserta didik tanpa memandang suku, warna kulit, atau latar budaya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa praktik diskriminasi rasial masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bentuknya tidak selalu berupa kekerasan fisik, melainkan hadir sebagai ejekan, stereotip, atau perlakuan berbeda yang dianggap lumrah oleh sebagian besar warga sekolah. Siswa yang berkulit lebih gelap, memiliki logat daerah tertentu, atau berasal dari kelompok etnis minoritas sering kali menjadi sasaran candaan yang dianggap “sekadar bercanda”, padahal memiliki dampak psikologis yang serius. Tidak jarang pula guru turut membiarkan hal tersebut karena menganggapnya sebagai dinamika biasa di antara siswa.
Dalam beberapa kasus yang muncul di Bangka Belitung, ditemukan bahwa siswa dari keluarga penambang timah tradisional misalnya, sering diejek karena kulit mereka lebih gelap atau karena pekerjaan orang tua. Di salah satu sekolah di Kabupaten Bangka, sejumlah siswa mengaku kerap dipanggil dengan sebutan yang merendahkan berkaitan dengan latar sosial-ekonomi keluarga mereka.
Dalam perspektif Teori Konflik, praktik diskriminasi ini dipahami sebagai upaya mempertahankan dominasi kelompok tertentu melalui kontrol akses terhadap kesempatan pendidikan. Di sekolah, hubungan kekuasaan ini dapat terlihat dalam menentukan siapa yang dipercaya mewakili sekolah pada perlombaan, siapa yang dianggap layak menerima rekomendasi beasiswa, hingga siapa yang dipilih tampil di kegiatan seremonial sekolah. Bias semacam ini seringkali tidak disadari karena sudah melekat dalam sistem nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dari sudut pandang Interaksionisme Simbolik, khususnya teori labeling, kita dapat memahami bahwa label negatif yang diberikan kepada siswa tertentu akibat latar belakang etnis atau sosialnya dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri. Ketika seorang siswa terus-menerus mendapatkan stereotip “kurang cerdas”, “pemalu”, atau “tidak cocok tampil di depan umum”, maka label tersebut bisa menjadi identitas permanen yang membatasi perkembangan dirinya.
Dampak dari praktik diskriminasi tersebut dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Beberapa siswa mengaku tidak direkomendasikan mengikuti Olimpiade Sains atau lomba akademik meskipun mereka memiliki nilai tinggi, hanya karena dianggap “kurang representatif”. Ada pula yang tidak dipilih menjadi petugas upacara atau perwakilan sekolah dalam acara resmi karena standar visual tertentu yang tidak tertulis. Dalam lingkungan pergaulan, kelompok siswa sering membentuk lingkaran pertemanan berdasarkan identitas etnis atau latar keluarga, sehingga terjadi pengelompokan sosial yang dapat memunculkan rasa terasing bagi mereka yang berbeda. Di kantin sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, fenomena pengucilan semacam ini terlihat jelas, tetapi jarang dibahas sebagai masalah bersama.
Melihat berbagai persoalan tersebut, perubahan di lingkungan sekolah menjadi sangat penting dan mendesak. Sekolah perlu menyusun strategi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif untuk menghentikan diskriminasi rasial. Salah satu langkah utama adalah memberikan pelatihan sensitivitas budaya bagi guru dan staf sekolah agar mereka memiliki kesadaran lebih tinggi mengenai pentingnya menghentikan candaan dan praktik diskriminatif, sekecil apa pun bentuknya. Selain itu, sekolah harus memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang tertulis dengan jelas, serta memastikan bahwa seluruh siswa memahami konsekuensi jika melakukan tindakan rasis. Budaya sekolah juga perlu diarahkan menjadi lebih inklusif, misalnya dengan mengadakan kegiatan yang mengangkat keberagaman budaya di Bangka Belitung, seperti tradisi Melayu, Tionghoa, Jawa, maupun suku-suku lain yang menjadi bagian dari identitas wilayah tersebut. Sekolah juga dapat menciptakan ruang dialog terbuka agar siswa berani berbicara tentang pengalaman diskriminasi tanpa takut dihakimi. Terakhir, keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi bagian penting karena anak-anak merefleksikan nilai yang mereka lihat di rumah dan lingkungan.
Pada akhirnya, rasisme di sekolah bukan hanya soal perilaku individu, melainkan persoalan struktural yang menghambat tujuan pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Jika sekolah terus membiarkan praktik diskriminasi, maka siswa yang menjadi korban akan kehilangan kepercayaan diri, kesempatan, dan potensi yang seharusnya dapat berkembang maksimal. Karena itu, sekolah di Bangka Belitung perlu menegaskan kembali perannya sebagai ruang aman bagi seluruh peserta didik, apa pun latar belakang mereka. Perubahan ini tidak dapat dilakukan dalam satu malam, namun merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa masa depan generasi muda tidak dibatasi oleh prasangka sosial yang seharusnya sudah ditinggalkan.

Penulis: Safia Andena, Mahasiswi Universitas Bangka Belitung